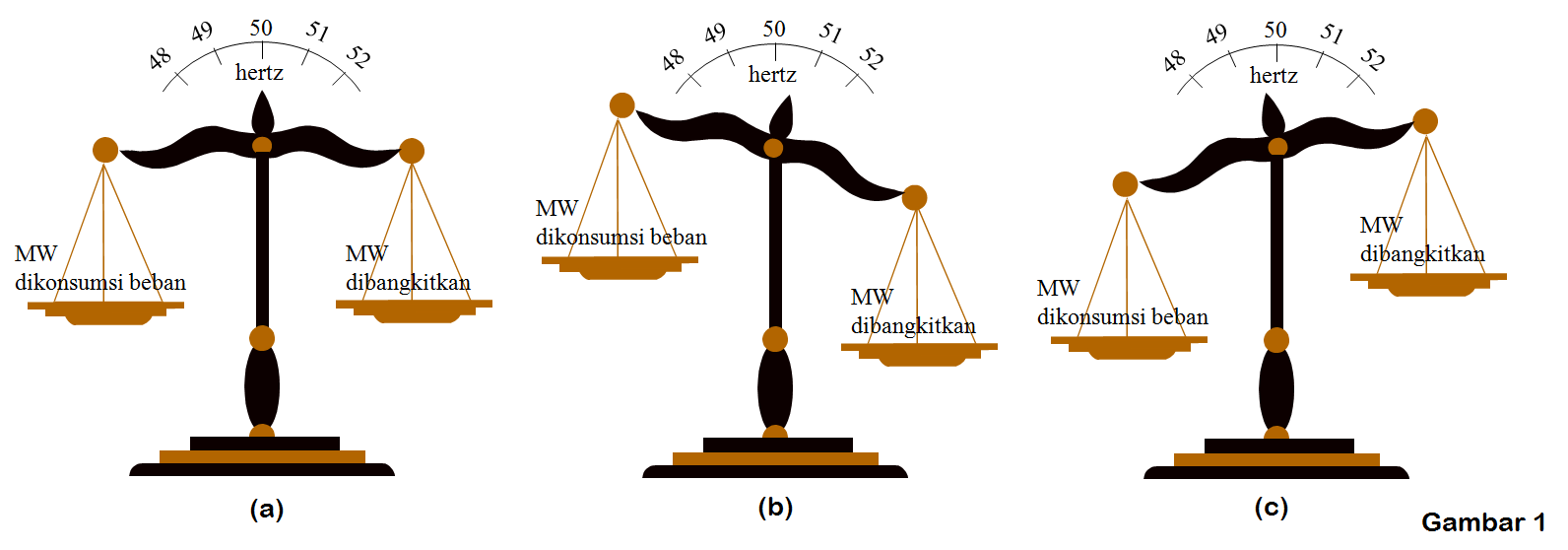Daya
Aktif, Daya Reaktif, dan Daya Kompleks
Konsep 3 daya ini sangat
mudah dijelaskan dalam model matematis (kalkulasi). Namun ketika berbicara
tentang apa sebetulnya 3 macam daya itu (hakikat atau fillosofinya), hal ini
menjadi sangat rumit. Konsep tersebut tidak hanya menyulitkan bagi seseorang
yang baru belajar elektrikal, namun yang sudah bergelut lama di bidang tersebut
mengalami semacam ‘dilema’. Antara paham dan tidak paham, setengah- setengah,
bingung, atau bahkan menganggap ketignya sebagai konsep di atas kertas saja.
Mungkin tulisan ini tidak akan menjelaskan konsep 3 daya dengan gambalang,
namun semoga sedikit membantu.
Seperti dikatakan dalam
deskripsi sebelumnya, daya kompleks (S, [VA]) merupakan penjumlahan vektor dari
daya aktif (komponen real, P, [watt]) dan daya reaktif (komponen imajiner, Q, [VAR]),
sehingga dituliskan S = P + jQ. Kita dapat memahami hal ini dengan mudah. Daya kompleks adalah
penjumlahan dua macam daya. Selanjutnya, perhatian kita tujukan pada setiap
komponennya, yaitu daya aktif dan daya reaktif.
Daya aktif (atau daya
nyata, daya real) adalah bentuk daya yang dapat diubah ke dalam kerja fisik.
Seperti motor (listrik ke putaran), heater
(listrik ke panas), dan lain-lain. Artinya, daya
listrik aktif dapat dikonversikan ke dalam bentuk daya lain dengan satuan yang
sama melalui mesin konversi energi. Maka konsep daya aktif juga mudah dipahami.
Namun ketika berbicara
tentang daya reaktif, kesulitannya akan segera muncul. Namun untuk mempermudah
pemahaman, pengenalan daya reaktif akan dilakukan dengan analogi yang sering
dipakai pada saat kuliah elektrikal. Kita kembali ke 3 macam konsep daya, yaitu
P, Q, dan S. 3 macam daya tersebut dianalogikan dengan segelas minuman bersoda,
yang berisi air soda dan buihnya. Air soda dianalogikan sebagai P, yaitu bagian
yang bisa dimanfaatkan dengan nyata. Buihnya dianalogikan sebagai Q, yaitu
bagian yang hanya digunakan sebagai pelengkap. Segelas penuh berisi air soda
dan buih, dianalogikan sebagai S. Hal ini digambarkan dalam gambar 3.
Dari analogi di atas, akan terasa bahwa daya reaktif adalah ‘daya pengganggu’, yang
keberadaannya sangatlah merugikan. Namun jika berfikir sejenak, power plant dan Pusat Pengatur Beban
melakukan pengaturan daya reaktif, pasti ada tujuannya. Yang menjadikan daya
reaktif bukanlah ‘daya pengganggu’, daya ini diperlukan.
Boleh
tidak suka, namun kita akan kembali membuat persamaan matematis dan
grafik-grafik. Misalkan sebuah beban induktif disuplai oleh sumber. Besar
tegangan dan arusnya adalah V dan arus I, yang masing masing memiliki besar 1
dan 0.75 satuan. Gelombang arus tertinggal 30°. Hal ini direpresentasikan pada gambar 4. Pada gambar 4a, digambarkan
jika gelombang tegangan (biru) dan arus (merah) dikalian, maka akan dihasilkan
gelombang daya semu, S (hijau).
Pada
persamaan sebelumnya, dijelaskan bahwa daya kompleks adalah penjumlah daya
aktif dan daya reaktif, S=P+jQ. Pada gabar 4b, gelombang S dipilah menjadi 2
porsi, yaitu daya aktif P (biru muda) dan daya reaktif Q (pink). Grafik P dan Q
diperbesar pada gambar 4c dan 4d.
Dari
gambar 4c, diperlihatkan bahwa grafik daya aktif selalu berada di daerah
positif. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai rata-ratanya adalah positif,
mengindikasikan aliran daya aktif adalah dari sumber ke beban (satu arah). Daya
aktif diproduksi sumber, dan dikonsumsi oleh beban.
Namun pada
gambar 4d, diperlihatkan grafik gelombang daya reaktif yang berosilasi pada
sumbu nol. Nilai sesaatnya kadang negatif dan kadang positif, mengindikasikan
bahwa aliran daya reaktif adalah memiliki dua arah. Dalam setengah siklus,
mengarah ke beban. Dan dalam setengah siklus berikutnya, akan mengarh ke
sumber. Nilai rata-rata grafik tersebut adalah nol, yang mengindikasikan bahwa
daya ini tidak dikonsumsi. Daya ini hanya bergerak ‘to and fro’, atau ‘mondar mandir’.
Dari analisis
grafik pada gambar 4, didapatkan bahwa daya reaktif adalah daya yang bergerak
dari sumber ke beban dan sebaliknya, suatu indikasi bahwa daya reaktif adalah
daya yang tidak dikonsumsi. Keberadaannya kekal. Hal ini mudah diterima dengan
mengaplikasikan Hukum Thermodinamika I, hukum kekekalan energi.
Namun
sangkalan akan kembali muncul jika kita belajar analisis jaringan. Entah apapun
metodenya, akan didapatkan istilah “Rugi Daya Reaktif”, yang seolah-olah daya
reaktif diserap oleh sistem transmisi (sebagaimana rugi-rugi panas, daya aktif
di kawat penghantar). Sebetulnya nilai tersebut adalah selisih daya reaktif
antara sumber dan beban. Dan ingat karakteristik saluran transmisi jika
dibebani, tergantung nilai SIL, ia dapat berupa komponen induktif atau
kapasitif.
Pada
bahasan sebelumnya, dituliskan persamaan bahwa P= VI cosφ dan Q=
VI sinφ, yang menjadikan keduanya mirip. Namun, gambar 5 menyajikan persamaan
untuk keduanya. Nilai terukur untuk P
adalah nilai rata-rata daya
aktif yang disalurkan dari sumber ke beban. Sedangkan Q adalah nilai maksimum daya reaktif yang bergerak bolak balik dari
sumber ke beban atau sebaliknya.
Uraian
sepanjang ini tidak menjelaskan sama sekali apa sebenarnya daya reaktif, kita
hanya membicarakan karakteristinya saja. Sering dikatakan bahwa daya reaktif
adalah unused power, namun secara pribadi saya tidak setuju dengan
istilah tersebut. Blackout di Ohio Utara 14 Agustus 2003 disinyalir sebagai
akibat dari rendahnya suplai daya reaktif.
Namun ada
beberapa hal yang bisa dituliskan dari uraian di atas mengenai daya reaktif:
1)
Daya reaktif akan muncul jika sistem tegangan
menggunakan gelombang bolak balik, dan terhubung ke beban reaktif (induktif dan
atau kapasitif).
2)
Daya ini bergerak dua arah antara sumber dan beban.
Sering diistilahkan Sloshing Power.
3)
Nilai terukurnya adalah nilai maksimum, bukan nilai
rata-rata. Meskipun memiliki persamaan yang mirip dengan daya aktif (berbeda
fungsi sinus dan cosinus), namun keduanya memiliki artin berbeda.
4)
Adalah suatu daya yang digunakan untu me-maintain tegangan, agar dapat
menyalurkan daya aktif di jaringan. Jika nilai daya rekatif cukup rendah, maka
tegangan akan turun dan tidak dapat menyalurkan daya aktif.
5)
Daya reaktif adalah daya yang berperan sebagai media
konversi energi, misal pada motor atau beban lain.
Dari
beberapa catatan tersebut, saya tertarik bahwa daya reaktif adalah daya yang
berperan dalam media konversi energi. Jika dianalogikan dalam sistem pembangkit
listrik tenaga uap (PLTU), daya reaktif adalah bentuk apresiasi atas kerja
keras water yang digunakan dalam
siklus PLTU. Water dipanaskan menjadi
uap, digunakan memutar turbin, didinginkan lagi menjadi water, dan dipanaskan lagi. Sebetulnya, bisa dikatakan bahwa water (dan bentuk turunannya) tidak
melakukan apa-apa, water hanya berfungsi
sebagai media konversi energi dari bahan bakar (batubara, udara, dan lain-lain)
menjadi putaran turbin.
Namun, paragraf terakhir adalah ide saja. Bukan ide, hanya sesuatu yang terlintas dan
sempat untuk dituliskan. Bisa didiskusikan kalau tidak tepat. Semoga bermanfaat.
Saat
ini, jika pembaca menanyakan “apakah daya reaktif itu?”, saya akan menjawab “saya
tidak tahu”.
Paiton, 9 April 2014. 13:59 WIB.